Near dan Karna Su Sayang sempat sangat viral dan mendapat penghargaan dari google karena menjadi konten yang paling banyak dicari oleh netizen. Ia seolah mengulang kesuksesan Gemu Fa Mi Re garapan Nyong Franco yang kerap jadi lagu wajib di acara-acara hiburan di berbagai kota di nusantara, mulai dari pesta nikah hingga senam para aparat militer.
Miu Mai, film garapan anak-anak muda Nian Tana meraih best form content untuk film dari regio Indonesia dalam Asian Academy Creative Awards yang berlangsung di Singapura. Setelahnya, tumbuh dengan perlahan tetapi subur komunitas-komunitas film di Maumere.
Kris Tomahu meraih posisi runner up X-Factor Indonesia 2024. Semua warga Maumere merayakannya. Ia mengulang prestasi yang sebelumnya diukir oleh Azizah di KDI 2015 dan Mario G. Klau pada ajang The Voice Indonesia 2016. Maumere memang tak pernah kehabisan talenta di bidang seni.
Sementara itu terjadi, sanggar-sanggar dan rumah-rumah budaya seperti Sutra Holak, Bliran Sina, Watu Bo, dan Lepo Lorun kian aktif menjalankan konservasi praktik dan produk-produk budaya. Mulai dari perawatan dan produksi kain tenun, ritual-ritual tradisional, sistem pengolahan kebun, dan kehidupan masyarakat adat yang organik hidup dan berusaha dilangsungkan di sanggar-sanggar ini.
Lepo-lepo (rumah adat) didirikan, kampung ditata. Meski tidak sepenuhnya memadai, kehadiran lepo-lepo dan kampung adat yang diusahakan oleh sanggar ini sedikit memberikan referensi visual-material yang bisa dirujuk, ketika muncul pertanyaan-pertanyaan tentang seperti apa arsitektur, fashion, dan tata kampung tradisional suku-suku di Kabupaten Sikka?
Kebudayaan kontemporer di Kabupaten Sikka seolah terbentang dalam dua spektrum situasi yang spesifik. Masing-masing seperti bergerak dengan arah yang saling bertolak belakang, atau bahkan kemana-mana.
Yang satu berkelana mengikuti arus zaman dan teknologi yang sedang pesat bergerak, sementara yang lain berusaha kembali ke akar, terus menggali atau bahkan tetap tinggal atas nama tradisi. Semuanya berlangsung dalam serba keterbatasan: keterbatasan infrastruktur, keterbatasan ekosistem dan pasar, keterbatasan perhatian dan apresiasi dari masyarakat, hingga keterbatasan pelaku yang menghidupinya. Namun, demikianlah karya kreatif. Kreasi tetaplah selalu perihal melampaui batasan-batasan.
Belakangan, sinergi dan kolaborasi antar pelaku-pelaku seni budaya ini bergerak cepat secara organik. Festival-festival komunitas digelar. Tur dan residensi ke sanggar-sanggar diupayakan terus berlangsung. Masing-masing melihat potensi satu sama lain. Yang modern melihat peluang untuk kembali ke akar dan menimba inspirasi serta wawasan tradisi. Yang tradisional melihat peluang melakukan inovasi dengan memanfaatkan teknologi dan skena trend modern.
Berhadapan dengan fenomena-fenomena ini, kita tentu perlu bertanya: dimanakah posisi pemerintah daerah? Sejauh mana pemerintah mengidentifikasi kebudayaan sebagai sesuatu yang penting dilibatkan dalam keseluruhan proses pembangunan? Apa itu kebudayaan (kontemporer) menurut pemerintah? Bagaimana sikap pemerintah terhadap para penggiat dan aktivis kebudayaan?
Amatan dan pengalaman dari para penggiat budaya dan pekerja kreatif di Kabupaten Sikka umumnya menilai bahwa pemerintah tidak punya visi yang jelas tentang pengembangan kebudayaan. Beberapa alasan dilontarkan.
Pertama, pemerintah tidak punya definisi yang utuh mengenai kebudayaan kontemporer Kabupaten Sikka. Kalaupun ada, itu tidak disosialisasikan kepada publik apalagi diejawantahkan secara maksimal dalam program-program dan aktivitas yang integral dengan seluruh proses pembangunan: misalnya dalam proses pendidikan generasi masa kini, tata kota, atau festival-festival seni budaya.
Bisa dicek, apakah ada pelajaran muatan lokal di sekolah-sekolah yang secara memadai memberi informasi dan pengetahuan tentang budaya di Kabupaten Sikka? Di konteks tata kota, seberapa banyak corak arsitektur khas Kabupaten Sikka dipakai dalam bangunan-bangunan publik? Seberapa banyak festival seni budaya yang diinisiasi pemerintah atau dikerjakan secara kolaboratif dengan penggiat seni lokal setiap tahunnya?
Jika banyak warga hari-hari ini mengeluh soal lampu di jalan-jalan dan kantor-kantor pemerintahan yang semrawut, itu tanda kalau pemerintah tidak melibatkan konsultan tata kota yang paham estetika dan arsitektur lokal dalam implementasinya.
Kedua, perbincangan mengenai kebudayaan kerap berubah sensitif manakala menyinggung sejarah kolonialisme di Sikka. Kolonialisme melalui bangsa kolonial (Portugis dan Belanda), Gereja, sistem monarki (kerajaan-kerajaan di Sikka) yang terus berlangsung hingga Orde Baru menyebabkan lemahnya lembaga dan komunitas adat.
Sejak lama hegemoni politik kebudayaan Sikka berlangsung dan meminggirkan kebudayaan-kebudayaan lain yang ada bersama di bumi Nian Tana. Hal itu secara otomatis melemahkan pelestarian apalagi pewarisan budaya dari generasi ke generasi.
Padahal, dalam praktiknya, kerap yang didefinisikan sebagai budaya adalah hal-hal yang berkaitan dengan adat dan tradisi. Banyak program revitalisasi praktik budaya dan cagar budaya. Namun sepertinya tidak dimanfaatkan secara tepat guna. Tiap tahun dinas hanya sibuk mengurusi pendataan sanggar-sanggar tanpa tahu untuk apa.
Kabupaten Sikka memikul beban kebudayaan yang besar. Dengan demikian rekonsiliasi atau apapun istilahnya yang lebih halus, sudah selayaknya dilakukan beriringan dengan penguatan komunitas, praktik, dan perlindungan aset-aset kebudayaan.
Ketiga, agakya logika pembangunan kebudayaan Sikka lebih bersifat profit daripada benefit. Pariwisata ditempatkan sebagai tujuan dari pada akibat. Sehingga penggalian, penghidupan dan transfer kebudayaan disepelekan, sementara keuntungan finansial diutamakan. Nomenklatur kebudayaan ada di Dinas Pariwisata, sehingga dalam banyak kasus, implementasi program-program kebudayaan harus seiring-sejalan dengan pariwisata.
Padahal Hilmar Farid, Dirjen Kebudayaan Republik Indonesia sendiri mengakui kalau pengembalian atas investasi (return of investment) kebudayaan yang menggunakan dana publik (negara) tidak bisa hanya diukur lewat dampak ekonomi dari pemanfaatan infrastruktur-infrastruktur utama (lewat penyewaan gedung, karcis, dll.), tetapi juga melalui dampak sosial (social return of investment) dan budaya (cultural return on investment) dari investasi yang dilakukan.
Sanggar-sanggar baru aktif jika ada turis dan berubah seperti kuburan yang sepi ketika tak ada pengunjung. Program pengembangan kapasitas seniman, pekerja kreatif, pelaku sanggar, tidak pernah serius diurus. Mungkinkah logika seperti ini diubah?
Keempat, implementasi dari visi dan logika yang rancu tersebut tertuang dalam gambaran umum RPJMD di bidang kebudayaan. Beberapa poin strategis berkaitan dengan pengembangan pariwisata dan kebudayaan yang direncanakan dalam RPJMD 2024-2026 misalnya memberi porsi sangat kecil di sektor Pengembangan Kebudayaan, yaitu dengan estimasi biaya mulai dari Rp.290,889,500 (2024), Rp.299,616,185 (2025), dan Rp.308,604,671 (2026). Itu pun seluruhnya ditujukan pada cakupan pengembangan objek pemajuan kebudayaan.
Ini jauh lebih kecil dari proyeksi pada sektor Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata (950,422,600 – 2024), Pemasaran Pariwisata (548,000,000- 2024), dan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (641,232,600 – 2025). Angka alokasi anggaran ini tentu akan naik tiap-tiap tahunnya.
Berkaitan dengan pembangunan sumber daya manusia dan peningkatan kapasitas pekerja kreatif seperti peneliti budaya, seniman, manager seni, talenta-talenta muda berbakat, festival budaya tak disinggung secara cukup eksplisit. Kalau pun disinggung, peluangnya hanya ada di sektor Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dengan proyeksi peningkatan persentase pengembangan sumber daya pariwisata dan ekraf yang kondisi awalnya diasumsikan berada pada angka 0%.
Mirisnya lagi, dengan logika demikian, sebenarnya setiap sumber daya kreatif dikondisikan untuk menjadi pelayan pariwisata, bukan pertama-tama menggalang penguatan identitas, peningkatan mutu manusia, dan pelestarian nilai-nilai serta penguatan ikatan sosial antarwarga masyarakat. Jadi, tidak salah kalau orientasi pembangunan kebudayaan kita masih kuat pada profit dari pada benefit.
Pemerintah daerah sibuk membangun objek dan menata hal yang fisik. Sementara mereka lupa pada penguatan kapasitas manusia sebagai aktor utama kebudayaan. Seperti kata Nyong Franco, ‘kita sibuk bikin senjata, tetapi lupa peluru dan siapa yang akan mengendalikannya’.
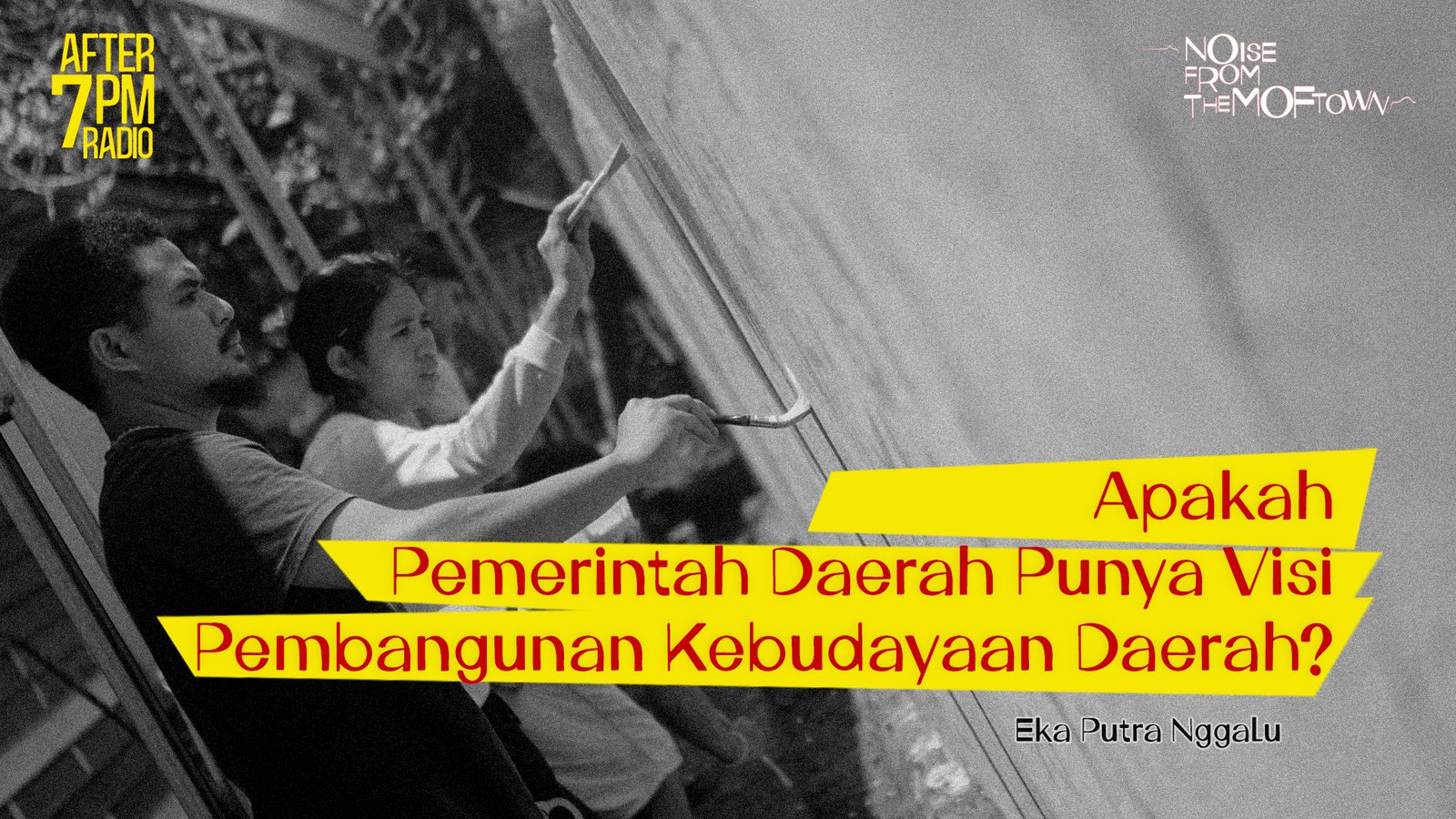






🙌🏻🔥🔥